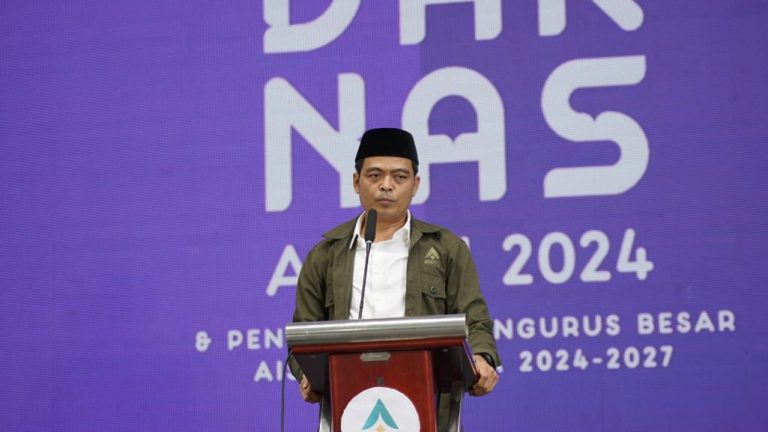Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian utang-piutang. Gadai merupakan suatu kepercayaan dari kreditur dan debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utang. Barang jaminan tetap menjadi milik debitur, namun dikuasai penerima gadai (kreditur).
————————
PRAKTIK pegadaian dibolehkan dalam Islam. Rasulullah SAW pun pernah melakukan transaksi gadai barang (baju besi) dengan seorang yahudi. Dalam gadai syariah yang terpenting dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan harapan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik riba’, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidaktransparanan) yang berakibat adanya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.
Istilah gadai dalam hukum Islam dikenal dengan Ar-Rahn. Dari segi istilah gadai (ar- Rahn) adalah suatu perjanjian atau akad pinjaman –meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan piutang. Akad gadai dalam Islam, tidak dibolehkan adanya praktik pemungutan bunga karena dilarang oleh syara’. Melainkan menggunakan biaya jasa, sebagai penerimaan dan labanya, yang dengan dikenakannya biaya jasa tersebut paling tidak dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasionalnya. Mekanismenya, ketika nasabah menyerahkan barang bergerak tidak terlepas dari biaya–biaya dan jasa penyimpanan (ijarah) serta perawatan. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
Gadai syari’ah selama ini sudah dilaksanakan (diterapkan) pada pegadaian syariah di Indonesia, namun belum masuk dalam perlindungan hukum pegadaian syari’ah di Indonesia. Maka, diperlukan kajian penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pegadaian Syariah dalam rangka merumuskan dan mengembangkan regulasi/hukum material gadai syari’ah.
Gadai syariah bila mengacu pada Pasal 21 KHES, dapat dilakukan berdasarkan asas: 1) Ikhtiyari/sukarela, 2) Amanah/menepati janji; 3) Ikhtiyati/kehati-hatian;4)Luzum/tidak berobah; 5) Saling menguntungkan; 6) Taswiyah/kesetaraan; 7) Transparansi; 6) Berkemampuan; 7) Taisir/kemudahan; 8) Beritikad baik; 9) Sebab yang halal; l0) Al-hurriyah (kebebasan berkontrak); dan 11) Al-kitabah (tertulis).
Pasal 22 menjelaskan rukun akad: a. Pihak-pihak yang berakad; b. Obyek akad; c. Tujuan-pokok akad; d. Kesepakatan. Pasal 25 tentang tujuan akad: 1. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. 2. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/ atau perbuatan.
Adapun kategori hukum akad berdasarkan Pasal 26, akad tidak sah apabila bertentangan dengan: 1. Syariat Islam; 2. Peraturan perundang-undangan; 3. Ketertiban umum; dan/atau 4. Kesusilaan. Pasal 27 menjelaskan hukum akad: a. Akad yang sah; b. Akad yang fasad /dapat dibatalkan; c. Akad yang batal/batal demi hukum.
Pasal 28: 1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya; 2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat; 3. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat syaratnya.
Adapun rukun akad (Pasal 373): 1. Rukun akad rahn terdiri dari: murtahin, rahin, marhun, marhun bih/utang, dan akad; 2. Dalam akad gadai terdapat tiga akad paralel yaitu: qardh, rahn, dan ijarah; 3. Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.
Pasal 374 menggambarkan bahwa para pihak yang melakukan akad rahn harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 375, Akad rahn sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin. Pasal 376: 1. Marhun harus bernilai dan dapat diserahkanterimakan; 2. Marhun harus ada ketika akad dilakukan. Pasal 377, Segala sesuatu yang termasuk dalam marhun, maka turut digadaikan pula. Pasal 378, Marhun dapat diganti dengan marhun yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 379, Marhun bih/utang yang dijamin dengan marhun bisa ditambah secara sah dengan jaminan marhun yang sama. Pasal 380, Setiap tambahan dari marhun merupakan bagian dari marhun asal.
Pembatalan akad rahn, Pasal 381: akad rahn dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh murtahin. Murtahin dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. Pasal 383: 1) Rahin tidak dapat membatalkan akad rahn tanpa persetujuan dari murtahin; 2) Rahin dan murtahin dapat membatalkan akad dengan kesepakatan. Pasal 384: Murtahin boleh menahan marhun setelah pembatalan akad sampai marhun bih/utang yang dijamin oleh marhun itu dibayar lunas.
Rahn dijelaskan pada Pasal 385: 1) Pada prinsipnya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya; 2) Apabila pemilik harta memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya secara mutlak; dan apabila pemilik harta memberi izin secara terbatas maka peminjam harus menggadaikannya secara terbatas; 3) Pemilik harta yang mengizinkan hartanya dijadikan jaminan dalam rahn harus mengetahui dan memahami risikonya; 4) Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikan kepadanya.
Hak dan kewajiban dalam rahn dapat dipahami pada Pasal 386: 1. Murtahin mempunyai hak menahan marhun sampai marhun bih/utang dibayar lunas; 2. Apabila rahin meninggal, maka murtahin mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dalam mendapatkan pembayaran utang. Pasal 387, Adanya marhun tidak menghilangkan hak murtahin untuk menuntut pembayaran utang, Pasal 388, Rahin dapat menuntut salah satu marhun apabila ia telah membayar lunas utang yang didasarkan atas jaminan marhun tersebut; Pasal 389, Akad rahn tidak batal karena rahin atau murtahin meninggal; Pasal 390, 1. Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan rahin yang meninggal; 2. Perbuatan hukum ahli waris dari rahin yang tidak cakap hukum dilakukan oleh walinya; 3. Wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin dari murtahin untuk melunasi utang;
Pasal 391: 1. Apabila rahin meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status marhun; 2. Marhun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan rahin; 3. Apabila rahin bermaksud menjual marhun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), marhun harus dijual meskipun tanpa persetujuan murtahin. Pasal 392, 1. Apabila pemberi pinjaman harta yang digadaikan meninggal dunia dan utangnya lebih besar dari kekayaannya, maka rahin harus segera membayar utang/menebus marhunyang telah dipinjam dari yang meninggal; 2. Apabila rahin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu membayar utang/menebus marhun, maka harta yang dipinjamnya/marhun akan terus dalam status sebagai marhun dalam kekuasaan murtahin; 3. Ahli waris dari pemberi pinjaman harta yang dijadikan marhun dapat menebus harta itu dengan cara membayar utang rahin.
Pasal 393 dapat dipahami bahwa 1. Apabila ahli waris rahin tidakmelunasi utang pewaris/rahin, maka murtahin dapat menjual marhun untuk melunasi utang pewaris; 2. Apabila hasil penjualan marhun melebihi jumlah utang rahin, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris rahin; 3. Apabila hasil penjualan marhun tidak cukup untuk melunasi utang rahin, maka murtahin berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya. Pasal 394, Kepemilikan marhun beralih kepada ahli waris apabila rahin meninggal.
Adapun hak rahin dan murtahin dapat dijelaskan dalam pasal pasal berikut: Pasal 395, rahin dan murtahin dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan marhun kepada pihak ketiga; Pasal 396, Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin rahin.
Penyimpanan marhun ada pada Pasal 397, Murtahin dapat menyimpan sendiri marhun atau pada pihak ketiga; Pasal 398, Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai; Pasal 399 Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak; Pasal 400, 1. Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain apabila penyimpan yang pertama meninggal, dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai. 2. Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai Apabila pemberi dan penerima gadai tidak sepakat; Pasal 401, Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.
Penjualan harta rahn adapat dilihat pada Pasal 402, Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerimagadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual harta gadainya; Pasal 403, 1. Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya; 2. Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah; 3. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan; 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.
Pasal 404, Apabila pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai; Pasal 405, Apabila penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi; Pasal 406, Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai; Pasal 407, Apabila yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya; Pasal 408, Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian apabila harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.
*Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung