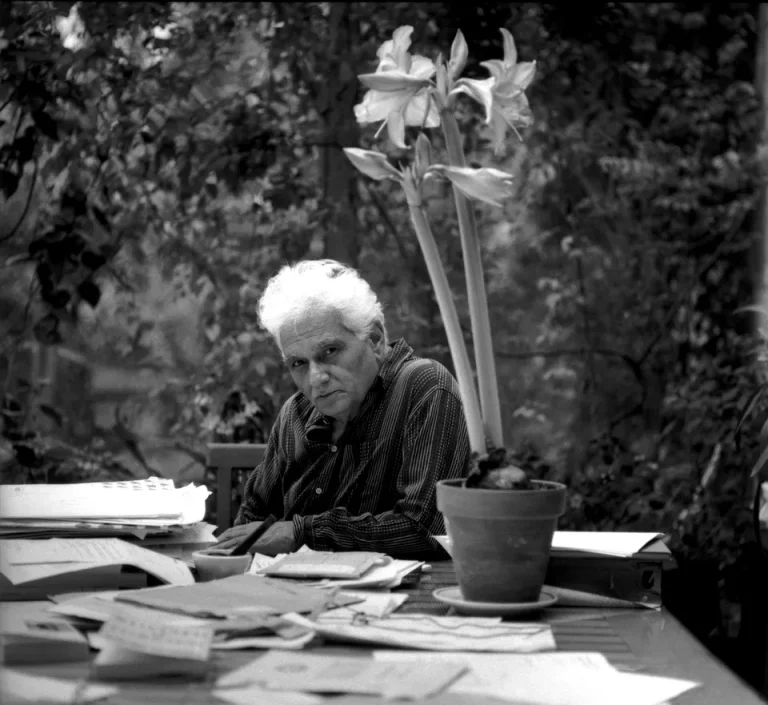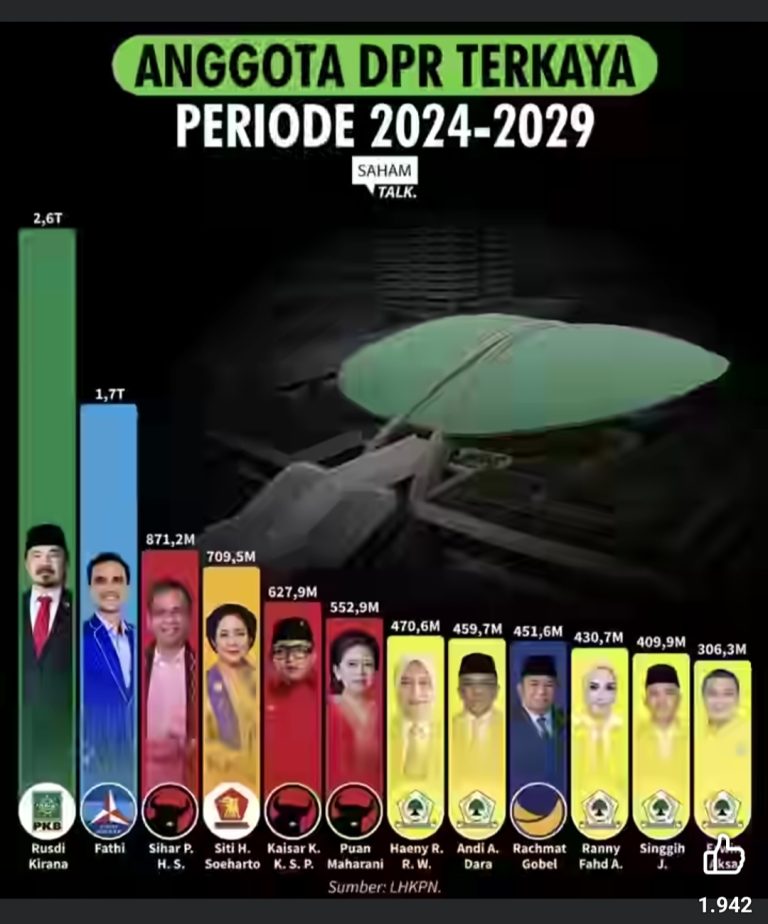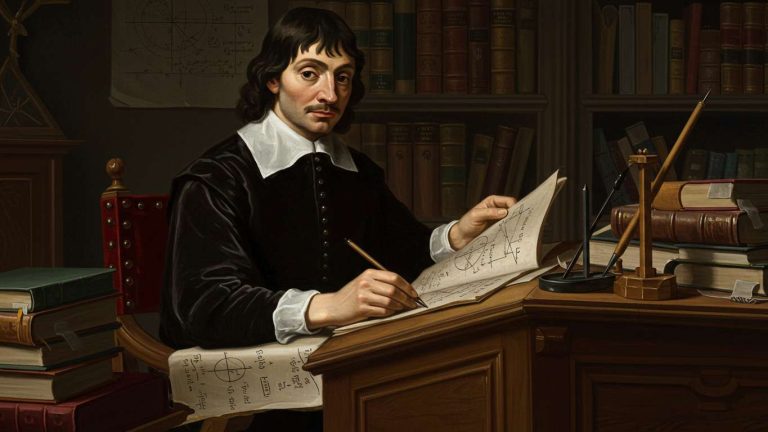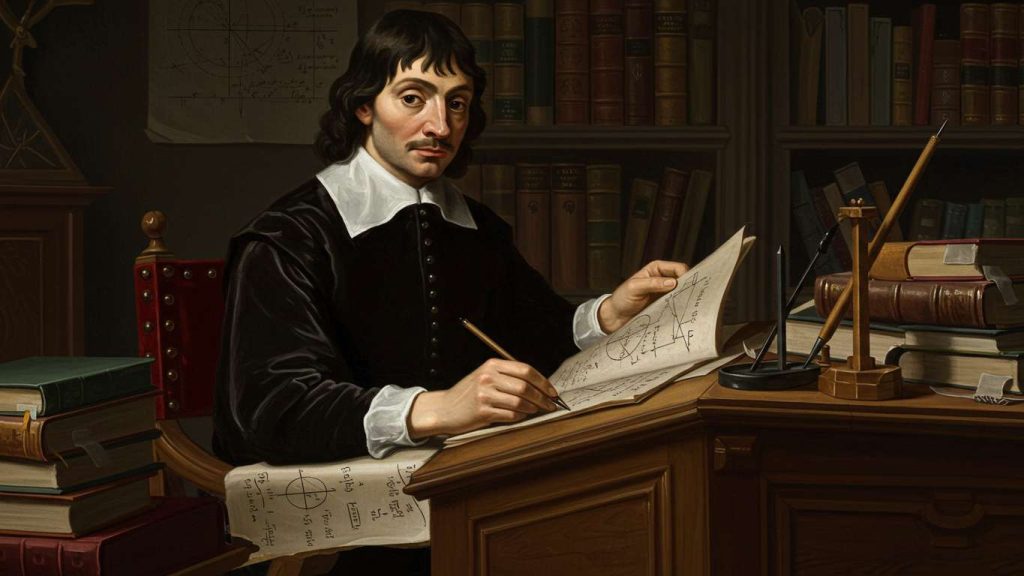
BANDUNG kanal31.com — Ketika dunia lama sedang runtuh dan dunia baru tengah mencari pijakan, lahirlah seorang pemikir yang kemudian disebut sebagai Bapak Filsafat Modern, Rene Descartes (1596- 1650).
Pemikiran Descartes tumbuh di tengah situasi Eropa sedang berada dalam masa transisi besar: sebuah dunia lama yang berakar pada otoritas Gereja dan filsafat skolastik Aristotelian mulai retak, sementara dunia baru yang ditandai oleh lahirnya sains modern mulai mencari bentuknya.
Secara sosial, Eropa masih sangat religius. Gereja Katolik, meski kekuasaannya mulai diguncang oleh Reformasi Protestan (abad ke-16), tetap menjadi institusi yang kuat dan dominan. Otoritas keagamaan mengatur bukan hanya kehidupan spiritual, tetapi juga kehidupan intelektual.
Universitas-universitas masih mengajarkan Aristotelianisme yang dilembagakan, di mana filsafat dipadukan dengan teologi dalam kerangka skolastik. Pengetahuan dianggap sebagai turunan dari otoritas dan tradisi, bukan hasil pencarian bebas.
Namun, pada saat yang sama, Eropa juga sedang diguncang oleh revolusi ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh seperti Copernicus, Kepler, dan Galileo memperkenalkan pandangan baru tentang kosmos yang mengguncang pandangan tradisional Gereja. Pandangan geosentris Aristoteles-Ptolemaios runtuh, digantikan oleh model heliosentris yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Penemuan-penemuan ini tidak hanya mengubah cara pandang manusia tentang alam, tetapi juga menumbuhkan keyakinan bahwa pengetahuan bisa dicapai melalui akal dan observasi, bukan semata dari otoritas.
Di ranah politik, Eropa dilanda ketegangan besar, salah satunya Perang Tiga Puluh Tahun (1618–1648), sebuah konflik panjang yang bermula dari perbedaan agama tetapi berkembang menjadi perebutan kekuasaan politik. Situasi ini menciptakan rasa gelisah dan ketidakpastian. Dalam konteks sosial semacam inilah Descartes tampil dan memilih jalan yang radikal: ia meragukan segalanya.
Dubito Ergo
Bagi Descartes, keraguan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kepastian. Ia menyebutnya sebagai keraguan metodis, suatu jalan yang dengan sadar ia pilih untuk menyingkirkan semua yang rapuh, semua yang hanya tampak pasti di permukaan, tetapi ternyata keropos di dasar. Keraguan baginya bukan penyakit jiwa yang melumpuhkan, melainkan sebuah alat bedah tajam untuk memisahkan yang sejati dari yang semu. Yang murni dari yang palsu. Ia menolak berhenti pada kebiasaan, pada dogma, pada otoritas masa lalu yang selama berabad-abad dianggap sebagai kebenaran tak tergugat.
Descartes, yang semenjak kecil dikenal rapuh secara fisik. Sering sakit-sakitan dan nyaris tidak pernah benar-benar sehat, menginginkan sebuah fondasi yang tidak bisa diguncang oleh siapa pun, tidak pula oleh waktu. Maka, seluruh keyakinan yang diwariskan oleh tradisi, seluruh pengetahuan yang ia peroleh dari indra, seluruh ajaran yang ia serap dari sekolah-sekolah filsafat ia letakkan di meja bedah keraguan. Descartes sungguh mengerti, bahwa indra bisa saja menipu, logika bisa menjerumuskan ke arah yang salah, bahkan mimpi pun sering mengecoh sebagai kenyataan.
Dan di tengah proses panjang keraguan itu, Descartes menemukan bahwa ada satu hal yang mustahil diragukan: “kenyataan bahwa dirinya sedang meragukan”! Meragukan adalah bentuk berpikir, dan berpikir adalah tanda adanya subjek yang berpikir. Maka, meski segala sesuatu ia singkirkan, ia tidak bisa menyingkirkan dirinya sendiri sebagai kesadaran yang sedang melakukan proses itu. Inilah titik kepastian pertama yang tak mungkin digoyahkan oleh siapa pun: “Dubito ergo. Cogito, ergo Sum” (Aku meragukan, Aku berpikir, maka aku ada.)
Ungkapan ini bisa terdengar sederhana, tetapi di dalamnya terkandung sebuah revolusi besar, manusia menemukan dirinya sebagai pusat pengetahuan, sebagai landasan bagi seluruh bangunan filsafat yang akan dibangun sesudahnya. Di sini, eksistensi tidak lagi bergantung pada dunia luar atau pengakuan orang lain, melainkan pada kesadaran diri yang tak bisa dihapuskan. Dengan itu, Descartes telah menyalakan api baru dalam sejarah pemikiran: bahwa kepastian sejati justru lahir dari keberanian untuk meragukan.
Kesadaran Eksistensial
Namun, cogito bukan sekadar rumus logis yang menjadi fondasi filsafat. Ia adalah sebuah kesadaran eksistensial yang dalam, bahwa keberadaan kita tidak pertama-tama ditentukan oleh apa yang kita miliki, oleh kedudukan yang kita tempati, atau oleh pengakuan orang lain, melainkan oleh kesadaran diri yang tak bisa diganggu gugat. “Aku berpikir, maka aku ada” berarti bahwa dalam sepi sekalipun, ketika segala hal di luar runtuh, kita tetap menemukan kepastian di dalam diri: selama kita masih berpikir, selama kita masih sadar, kita masih ada.
Di sinilah pesan Descartes menjadi relevan hingga hari ini. Dunia modern yang lahir dari warisannya adalah dunia yang penuh dengan keraguan: keraguan terhadap tradisi, terhadap institusi, bahkan terhadap makna hidup itu sendiri. Namun, dari keraguan itulah manusia belajar berdiri di atas kakinya sendiri, menemukan pijakan bukan di luar, melainkan di dalam. Cogito adalah peringatan halus bahwa kepastian sejati tidak bisa diberikan oleh dunia luar, tetapi harus lahir dari kedalaman diri.
Lebih jauh lagi, cogito menyingkap bahwa manusia adalah makhluk kesadaran, dan kesadaran itu adalah sumber kebebasan. Sebab hanya makhluk yang sadar akan dirinya yang dapat memilih, menimbang, dan menentukan arah hidupnya. Tanpa kesadaran itu, kita hanyalah bagian dari mekanisme dunia, bergerak tanpa tahu ke mana, terombang-ambing tanpa kendali. Tetapi dengan kesadaran, kita menyadari keberadaan kita, dan dari situ lahirlah tanggung jawab, bahwa kita bukan hanya ada, melainkan dipanggil untuk memberi makna pada keberadaan itu.
Dengan demikian, cogito Descartes bukan sekadar landasan bagi filsafat modern, melainkan juga cermin eksistensial bagi kita. Ia mengajarkan bahwa keraguan bisa menjadi jalan, kesadaran adalah kepastian, dan keberadaan sejati bukanlah sekadar “hidup” di dunia, melainkan hadir dalam kesadaran penuh atas diri. Dari titik ini, manusia modern bisa belajar, bahwa “berpikir adalah tanda kita ada, tetapi memberi makna pada pikiran adalah tanda kita sungguh hidup”.
Realitas yang Terbelah
Namun, penemuan itu tidak berhenti pada kesadaran diri. Descartes juga membelah realitas menjadi dua: res cogitans (substansi berpikir, yakni jiwa, pikiran, kesadaran); dan res extensa (substansi yang dapat diukur, yakni dunia material, ruang, dan benda). Pemisahan ini di kemudian hari menjadi dasar cara pandang modern terhadap dunia: bahwa alam dapat dipelajari, dipetakan, dihitung, dan dikuasai oleh hukum-hukum mekanistik, sementara kesadaran manusia tetap menjadi misteri yang tak bisa direduksi hanya pada materi.
Di sinilah pengaruh Descartes bagi lahirnya rasionalisme modern menjadi nyata. Ia memberikan manusia kepercayaan baru bahwa akal adalah kompas utama pengetahuan. Rasionalitas bukan sekadar alat, melainkan cahaya yang menyingkap kebenaran. Dari tangannya lahir gagasan tentang metode deduktif, tentang kejelasan (clarity) dan distingsi (distinctness) sebagai tanda-tanda kebenaran. Semua ini bukan hanya mengubah filsafat, melainkan juga menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan modern yang kita kenal sekarang.
Para penerusnya seperti Spinoza dan Leibniz mengembangkan lebih jauh semangat rasionalisme ini: keyakinan bahwa dengan akal, manusia mampu menyingkap hukum-hukum semesta dan bahkan mendekati kebenaran universal. Meski kemudian muncul tantangan dari empirisisme (yang menekankan pengalaman inderawi) warisan Descartes tetap menjadi tiang penyangga peradaban modern.
Dan jika kita berhenti sejenak untuk merenungkan, kita akan melihat betapa ungkapan “Cogito, ergo sum” bukan sekadar batu loncatan sejarah filsafat, melainkan juga cermin bagi kehidupan kita hari ini. Di tengah dunia yang penuh keraguan, banjir informasi, dan pergulatan identitas, Descartes mengingatkan, “yang paling mendasar bukanlah apa yang orang lain katakan, bukan pula apa yang dunia tetapkan, melainkan kepastian yang kita temukan dalam kesadaran diri”. Selama kita berpikir, kita ada. Selama kita sadar, kita memiliki pijakan.
Descartes, dengan seluruh keterbatasannya, telah menanamkan benih kesadaran modern, bahwa manusia adalah pusat dari pencarian pengetahuan, dan akal adalah jembatan menuju terang. Ia tidak hanya membangun sebuah sistem filsafat, tetapi juga menyodorkan cermin di mana kita melihat keberadaan kita sendiri. Sebuah cermin yang, hingga hari ini, masih memantulkan pertanyaan yang sama, apakah kita sungguh-sungguh berpikir?! Allahu a’lam bi Showab.
Radea Juli A. Hambali Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung