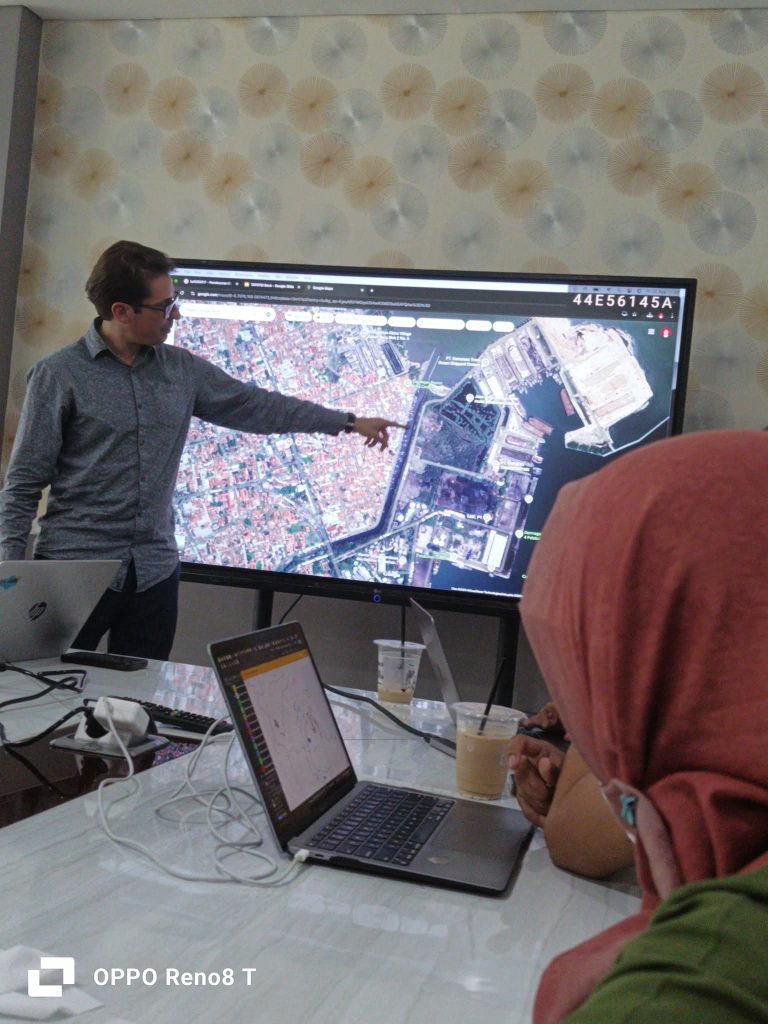BANDUNG kanal31.com — Tak sedikit orang berpura-pura kaget ketika mendengar kabar perselingkuhan bos dengan sekretarisnya, atasan dengan bawahannya, dokter dengan perawatnya, dosen dengan mahasiswanya, ustadz dengan santrinya dll, seolah itu tragedi besar yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Padahal, fenomena itu bukan perkara hitam-putih, bukan pula semata-mata soal moral atau aib agama, melainkan tentang dinamika manusia yang sedang mencari tempat bagi hasratnya yang dibungkam oleh norma, tapi terus bergejolak dalam tubuh dan batin.
Mari kita bicara jujur. Perempuan berusia muda, gadis berstatus sekretaris, ibu muda sebagai karyawati atau guru, mahasiswi yang sedang mekar, itu semua berada di usia biologis yang sedang hangat, usia gejolak syahwat tak bisa dibungkam hanya dengan dalil. Di sisi lain, banyaknya pria berusia matang, memiliki posisi kuasa sekaligus daya tarik tertentu: stabil secara finansial, matang secara verbal, dan punya otoritas intelektual yang menarik. Kombinasi antara hasrat dan kekaguman adalah bahan bakar paling mudah untuk menyalakan api relasi yang lebih intim dari sekadar hubungan kerja atau urusan akademik.
Tapi ini bukan hanya soal usia dan hasrat, ini juga tentang struktur sosial dan budaya yang memenjarakan gejolak hasrat. Laki-laki diberi naluri berpoligami oleh fitrahnya, oleh biologisnya, tapi di saat yang sama dihantam oleh sistem monogami yang menjadikan keinginan lebih dari satu dianggap buruk. Ketika keinginan itu muncul, masyarakat langsung mencap: tidak setia, tak bermoral, atau doyan perempuan. Padahal, yang sering tak disadari: justru karena tak ada saluran yang sah dan sehat bagi hasrat itu, ia mencari jalannya sendiri secara diam-diam.
Banyak istri yang mencintai suaminya tapi tak sanggup memahami kompleksitas biologis dan psikologis lelaki. Ketika suaminya gelisah dan mulai terdistraksi oleh pesona lain, mereka menganggap itu bentuk pengkhianatan, bukan kegelisahan eksistensial. Sementara di luar sana, perempuan muda hadir dengan semangat mengagumi, menyimak, memberi perhatian—hal-hal yang jarang lagi diterima lelaki di rumahnya yang sunyi dan penuh tuntutan.
Lalu muncullah peristiwa: tempat kerja jadi pertemuan rutin, kantor jadi ruang curhat, konsultasi akademik berubah jadi pelarian emosional, dan sebelum sadar, keduanya sudah larut dalam relasi yang tak lagi netral. Kita bisa marah, bisa mencaci, tapi kita juga bisa menyelami lebih dalam—bahwa ini bukan sekadar dosa, tapi juga jeritan jiwa yang tak punya ruang untuk menyalurkan fitrahnya secara manusiawi dan dewasa.
Banyak yang pura-pura alim mengharamkan poligami atas nama kesetiaan, padahal di belakang layar mereka menyimpan dua-tiga relasi diam-diam. Poligami yang seharusnya menjadi pintu syar’i untuk menyelamatkan syahwat justru dipenjara oleh stigma dan hukum sosial yang munafik. Maka ketika pintu halal ditutup, jalan haram pun dibuka oleh represi dan ketakutan terhadap omongan orang.
Fenomena ini bukan hanya soal moral individu, tapi juga tentang sistem sosial yang gagal memberi ruang aman bagi manusia untuk menjadi dirinya sendiri, mencintai tanpa merasa berdosa, dan jujur pada kerumitannya sendiri. Pria matang dan perempuan muda sering jadi korban dari represi sosial terhadap hasrat, bukan semata-mata pelaku kebejatan.
Tak perlu cepat menghakimi. Sebab dalam tubuh tiap manusia, ada kegelisahan yang tak selalu bisa diceritakan. Dalam batin tiap lelaki, ada pergulatan antara cinta yang ingin suci dan hasrat yang ingin hidup. Mungkin yang perlu kita lakukan bukan menghukum, tapi menciptakan ruang perbincangan yang jujur dan berani—tentang seksualitas, cinta, poligami, dan kemanusiaan.
Dan jangan lupa, Tuhan Maha Tahu keruwetan hati kita. Kadang, yang kita sebut sebagai dosa adalah teriakan sunyi dari jiwa yang lama tak dimengerti. Huh!!
Moeflich H. Hart, Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung.