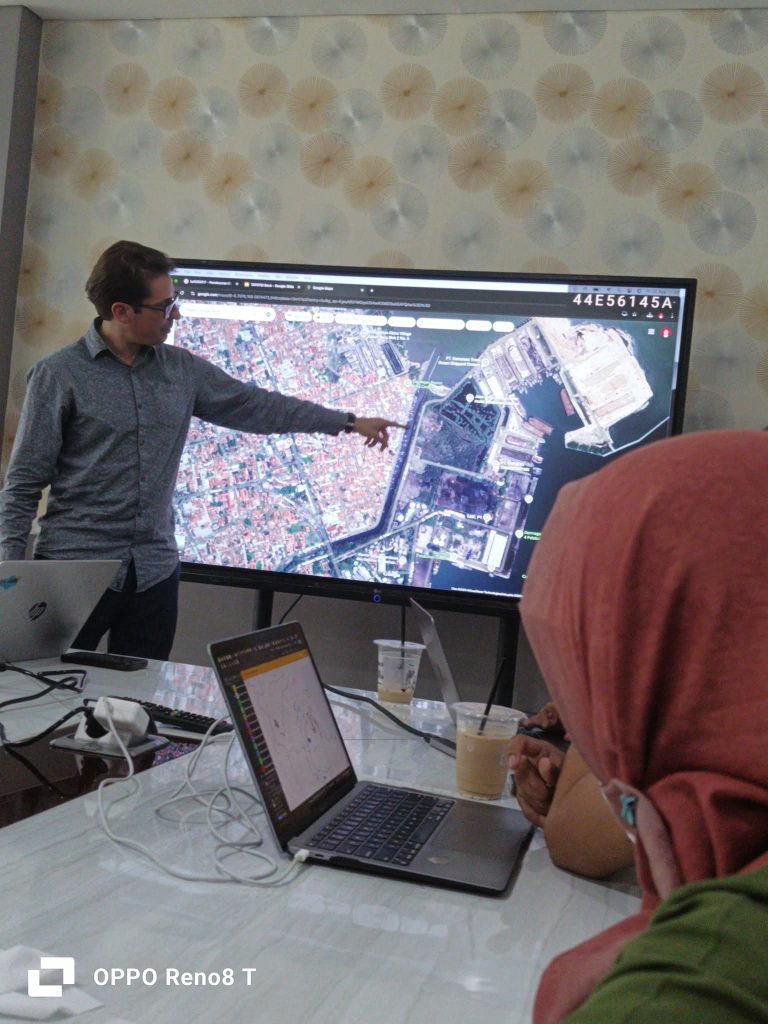BANDUNG kanal31.com — 3M. Selain Maung (Bandung) dan Milan, Madrid adalah klub sepak bola yang saya suka. Dan salah satu pemain Los Blancos yang kerap menarik perhatian saya adalah Luca Modric. Ia berperan sebagai gelandang, tapi melampaui sekadar gelandang, Modric dalam penilaian saya adalah arsitek di lapangan yang berpikir.
Sejak kedatangannya dari Tottenham Hotspur pada 2012, dengan keraguan yang menyertainya, bahkan sempat disebut sebagai “pembelian terburuk ” oleh sebagian media Spanyol. Pelan tapi pasti, Modric menjelma menjadi nyawa di lini tengah Madrid. Tiga belas tahun bersama Los Blancos, pria kurus dari Kroasia itu menjahit sejarah dengan kerja keras, keanggunan, dan ketulusan.
Tak terhitung jumlah pertandingan di mana Modric menjadi poros perubahan. Bersama Madrid, Modric mempersembahkan lebih dari sekadar trofi: lima Liga Champions, tiga La Liga, empat Piala Dunia Antarklub, dan sederet penghargaan lainnya. Ia juga mendapat penghargaan Ballon d’Or 2018, satu-satunya pemain dalam satu dekade yang berhasil memecah dominasi Messi dan Ronaldo. Saya kira, warisan Modrić melampaui itu. Ia adalah jembatan dari generasi emas ke generasi baru. Ia bermain bersama Ronaldo dan Benzema, lalu bersama Bellingham dan Valverde.
Bersama Toni Kroos dan Casemiro, ia membentuk salah satu trio lini tengah terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Mereka bukan sekadar pemain hebat tapi adalah simfoni yang bergerak dalam tiga nada. Casemiro sebagai tembok baja yang mematahkan tiap serangan lawan, Kroos sebagai mesin akurasi yang mengalirkan bola dari kedalaman, dan Modric adalah napas dan imajinasi dari ketiganya. Dialah yang menghubungkan, menjahit ruang, dan menyulam ritme. Mereka saling melengkapi: kekuatan, kecerdasan, dan keindahan.
“Luka is a magician,” ujar Zinedine Zidane, pelatih yang pernah memolesnya menjadi lebih dari sekadar gelandang. “Ia melihat permainan dua detik lebih cepat dari semua orang di lapangan,” begitu Zidane menambahkan. Sementara menurut Carlo Ancelotti, dalam salah satu wawancara pasca laga Liga Champions, menyebutnya “simfoni dalam bentuk manusia.”
Memang begitulah cara Modric bermain: tidak mencolok, tapi nyaris sempurna. Lewat satu sentuhan luar kaki, ia bisa memecah pertahanan lawan paling rapat. Lewat satu pergerakan kecil, ia membuka ruang untuk gelombang serangan. Dalam sepak bola yang makin didominasi fisik dan kecepatan, Modrić adalah pengingat bahwa kepala dan kaki harus tetap jenius.
Di akhir pertandingan melawan Real Sociedad, dengan skor kemenagan 2-0, Modric pamit. Tampak ada kesedihan di raut wajahnya. Saya kira, Madrid tidak hanya kehilangan pemain, tapi juga kehilangan ruh dari gaya bermain yang memadukan rasa dan estetika. Terasa ada ruang kosong yang tidak bisa segera diisi. Santiago Bernabéu tidak hanya kehilangan seorang pemain, tapi juga kehilangan detak lembut yang selama ini menjaga ritme permainan.
Legenda hidup seperti Modric tak pernah benar-benar pergi. Ia akan hidup abadi dalam setiap tepuk tangan yang mengiringi assist menawan, dalam setiap remaja yang belajar bagaimana memberi umpan dengan mata, bukan hanya dengan kaki. Ia akan tetap tinggal dalam ingatan, dalam arsip permainan, dalam setiap benak anak-anak muda yang akan tumbuh menirukan umpan trivela-nya, dan dalam bisikan pelatih yang berkata, “Mainlah seperti Luka.”[]
Radea Juli A Hambali, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati