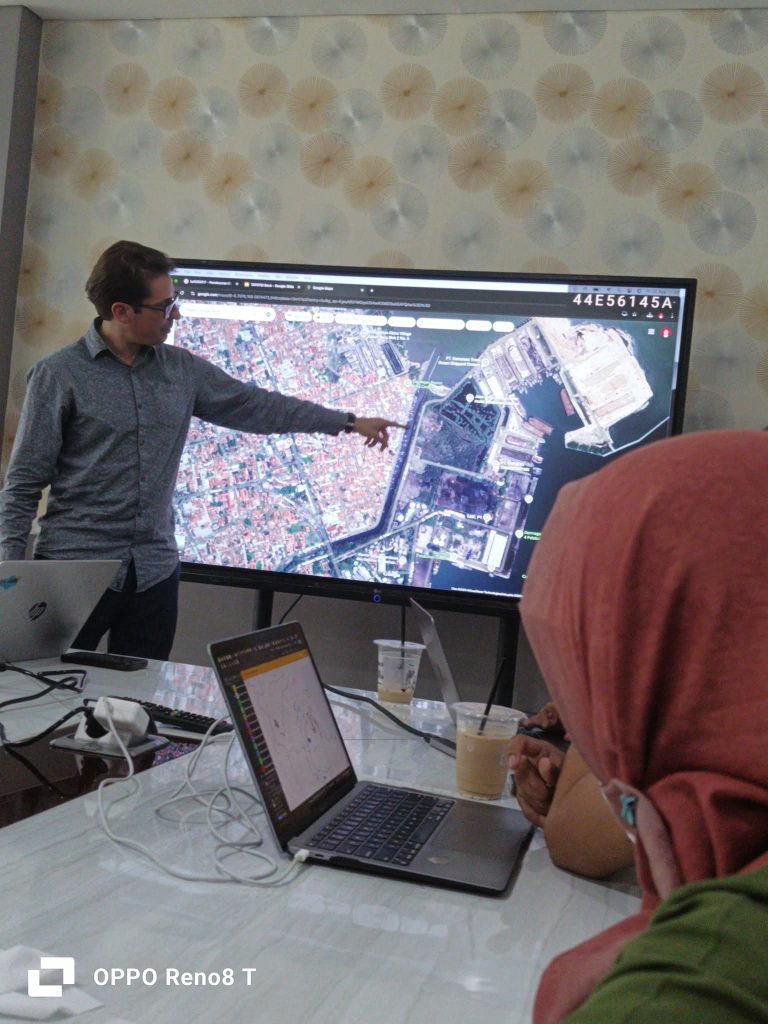BANDUNG Kanal31.com — Dalam setiap kata yang kita ucapkan, dan pada setiap makna yang kita yakini hadir secara utuh, mungkin sebenarnya ada celah yang tak kita sadari dan kita luput mengamatinya –sebuah ruang dimana makna justru menghindar, menunda kehadirannya. Di sanalah, barangkali, Jacques Derrida menunggu. Bukan sebagai penjaga pintu kebenaran, tapi sebagai penanya yang setia, yang dengan sabar menggugah kesadaran kita untuk tidak cepat-cepat merasa puas dan selesai dengan pemahaman.
Pemikiran Derrida adalah ajakan untuk mengendap sejenak, di antara yang terang dan yang samar, antara yang diucap dan yang tersisa. Ia hendak mengguncang keyakinan kita pada makna yang stabil dan utuh. Ia mengguyahkan kepercayaan lama kita bahwa bahasa mampu merepresentasikan bahkan menjinakkan kenyataan.
Bagi Derrida, tidak ada makna yang hadir sepenuhnya, seutuhnya –ia selalu datang tertunda, berbeda, dan terserak dalam jaringan kata-kata yang saling menandai, saling menghindari. Ia menyebut ini sebagai différance, sebuah istilah yang tidak ingin selesai dalam arti, karena sejak awal memang dimaksudkan untuk menolak keutuhan dan kesempurnaan makna.
Derrida tidak menghancurkan teks, melainkan menyimak dan mendengarkan apa yang tersembunyi di balik teks, apa yang mungkin ditekan oleh struktur, oleh budaya, oleh warisan metafisika Barat yang selalu mendewakan pusat, asal, dan kehadiran. Ia menyusuri jejak-jejak makna yang tersembunyi di pinggir, yang terpinggirkan, yang terdiam.
Dalam oposisi-oposisi biner seperti laki-laki/perempuan, rasional/irasional, Barat/Timur, ia menemukan praktek kekuasaan yang bekerja secara halus seolah tak terdeteks, menempatkan satu di atas yang lain, dan menyebut itu sebagai “kebenaran”. Tapi kebenaran macam apa yang lahir dari ketimpangan?
Dengan dekonstruksi, Derrida mengajak kita untuk membuat “tanda kurung” dengan menunda penghakiman. Dekonstruksi tak sekadar membongkar, tetapi mengajak kita untuk membaca ulang, meraba kemungkinan-kemungkinan baru dalam teks dan dalam cara kita melihat dunia. Ini bukan sekadar proyek akademik, melainkan sikap hidup: bahwa makna tidak pernah bisa mutlak, dan bahwa setiap kehadiran selalu membawa bayangan dari ketidakhadiran.
Ada yang menganggap pemikirannya rumit, bahkan membingungkan. Tapi barangkali kebingungan itu bukan kegagalan, melainkan pintu untuk kerendahan hati –untuk mengakui bahwa kita tidak selalu tahu, dan bahwa mungkin tidak ada satu pun cara tunggal untuk memahami apa pun.
Di dunia yang sering tergesa-gesa dalam menyimpulkan, Derrida dengan dekontruksinya menawarkan sikap dan ketekunan untuk meragukan. Dalam dunia yang gemar memberi label, ia membujuk bahkan mengajak kita untuk mendengar yang tak terdengar, melihat yang tersembunyi, membaca yang tersirat.
Mungkin, Derrida tidak memberikan jawaban pasti dan memuaskan. Tapi justru di situlah nilainya: ia mengajarkan kita seni bertanya. Dan bukankah dalam setiap pertanyaan yang sungguh-sungguh, kita sebenarnya sedang mendekati sesuatu yang lebih jujur dari sekadar jawaban? Allahu a’lam
Radea Juli A. Hambali, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung