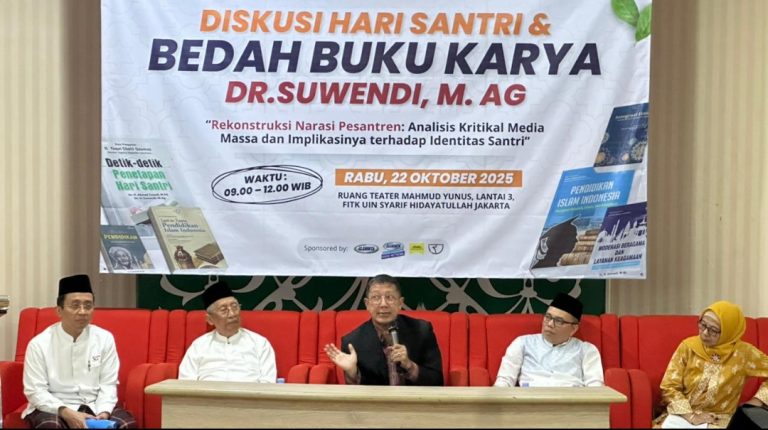BANDUNG Kanal31.com –Ketika melihat tayangan “Xpose Uncensored” di Trans7 yang memicu kontroversi dan kegaduhan di media sosial, sebagai santri, saya geram, marah, tidak terima, sosok Kiai yang sangat dimuliakan di kalangan pesantren, dinarasikan secara tidak proporsional dan direndahkan dengan intonasi dan diksi suara bernada sinis negatif.
Saya menduga, orang-orang yang berada di belakang program tersebut tidak mengenal Kiai dan pondok pesantren secara utuh. Sebagai orang pesantren, saya tahu betul bahwa perjalanan pesantren adalah cerita tentang khidmah, kemandirian, perjuangan bertahan hidup (survival) dan terus berkembang tanpa mengandalkan dan terlalu berharap bantuan pihak lain, termasuk dari negara.
Mendirikan dan mengajar di pesantren adalah perjalanan “hening”. Para kyai melakukan kerja sukarela, berjuang sepenuh hati tanpa terlalu berharap imbalan materi. Di lingkungan pesantren ada satu prinsip nilai yang dipegang teguh oleh para kyai yaitu: “jika kyai berhadap diberi (toma), maka padanya tidak melekat kehormatan ilmu dan dia tidak akan mampu menyuarakan kebenaran”.
Di tengah pergaulan bisnis, politik, dan akademik yang semakin bising dengan hiruk pikuk transaksi dan hitung-hitungan royalti dan remunerasi, saya semakin kagum dan hormat pada para “kiai kampung” yang sudah mengamalkan prinsip voluntarisme dan kerja “pro bono”, sebelum para “aktivis kota” mempopulerkannya.
Namun, bukan berarti kiai tidak mempunyai sisi lemah dan tidak boleh dikritik. Pondok pesantren juga mempunyai kekurangan yang perlu dibenahi. Saat ini, tidak ada lembaga pendidikan yang moderen sekalipun yang sempurna. Kritik juga perlu. Tapi kritik seharusnya dilakukan dengan niat tulus untuk memperbaiki, bukan untuk mempermalukan dan mencari sensasi.
Dalam tayangan kontroversial itu, ada adegan santri memberi amplop kepada kiai dan dinarasikan seolah tradisi itu bersifat “eksploitatif-transaksional”. Padahal dalam tradisi pesantren, hal itu lebih dimaknai sebagai bentuk penghormatan, ekspresi rasa syukur, khidmah, dan adab kepada guru.
Di kalangan pesantren dan orangtua santri ada satu ajaran nilai yang cukup kuat diyakini bahwa keberhasilan belajar seorang anak (santri) tidak hanya ditentukan oleh ikhtiar belajar si anak, tapi juga oleh usaha orang tuanya. Seseorang yang menginginkan anak cucunya menjadi orang berilmu (‘alim) maka dia harus memerhatikan dan menyantuni ahli ilmu (kyai, guru, atau para pengembara yang sedang menuntut ilmu) dan ahli ibadah.
Satu ajaran yang sangat penting dan relevan saat ini, di tengah fenomena pragmatisme orangtua, berkurangnya kepedulian dan partisipasi orangtua dalam pendidikan, serta hilangnya rasa hormat orangtua kepada para pendidik (guru).
Bentuk perhatian dan santunan tersebut, pada beberapa pesantren antara lain diekspresikan dengan pemberian amplop (uang), barang, makanan dari orangtua santri kepada kiai/ustadz, baik diberikan secara langsung atau dititipkan kepada santri. Biasanya pada saat orangtua santri berkunjung ke pesantren atau saat santri kembali ke pesantren setelah liburan.
Pesantren bukan hanya tempat belajar agama. Ia juga ruang sosial yang menanamkan moral, disiplin, solidaritas, dan nilai kemanusiaan. Gus Dur menyebutnya sebagai sub kultur yang unik, yang memiliki tradisi dan tata nilai tersendiri yang “khas”. Tradisi pesantren tidak dapat dipahami hanya lewat potongan video atau wawancara singkat. Dibutuhkan waktu, pendalaman makna, plus rasa hormat untuk benar-benar memahami.
Dalam mengkaji tradisi dan nilai-nilai pesantren, seorang jurnalis harus netral, agar informasinya objektif dan tidak bias. Jurnalisme milenial bukanlah sebatas kerja-kerja jurnalistik yang beradaptasi dengan piranti teknologi digital, berani memproduksi berita provokatif yang viral dan “nakal”. Jurnalisme milenial adalah cara kerja jurnalistik yang menghargai tradisi, nilai, dan kearifan lokal, serta mampu memadukan keterampilan teknis, pengetahuan dan nilai-nilai spiritual.
***
Entah disengaja atau tidak, masalah utama narasi tentang kiai dan pesantren dalam program “Xpose Uncensored” Trans7 itu adalah hilangnya “konteks”. Potongan video tidak pernah netral. Ketika disunting dengan cara tertentu, maknanya dapat bergeser sangat jauh dari konteks-nya. Setiap gambar dan kalimat dalam berita, mempunyai makna dan dampak. Tradisi yang seharusnya dimaknai sebagai etika menjadi tampak aneh bagi yang tidak mengenalnya secara utuh.
Sangat disayangkan, framing seperti itu berisiko menciptakan “jarak” antara publik dan pesantren, lembaga pendidikan indigenous (khas) yang diakui sebagai local genius dalam pendidikan nasional karena kemandirian dan keunggulannya—dengan tradisi keilmuannya yang spesifik, melakukan transmisi dan internalisasi nilai-nilai moral kepada masyarakat.
Saya tahu, media mempunyai kebebasan, ada prinsip kebebasan pers untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa tekanan dari pihak manapun. Namun, kebebasan itu datang bersama tanggung jawab. Sebagai mantan aktivis pers mahasiswa, saya tidak habis mengerti, ada produk jurnalistik sebodoh dan seceroboh itu.
Dari pilihan nama program “Xpose Uncensored” sepertinya mereka ingin disebut sebagai kelompok jurnalis “kritis-pemberani” melawan “sensor” dengan menyematkan kata “uncensored”. Namun, sepertinya mereka belum khatam belajar “jurnalisme kritis” karena mengabaikan riset kritis, prinsip verifikasi, komprehensif, seimbang dan proporsional dalam kerja-kerja jurnalistiknya.
Saya mengerti bahwa cara kerja media terkadang serba cepat dan penuh tekanan, namun hal itu tidak lantas mengabaikan etika jurnalistik, profesionalisme dan idealisme dalam berkarya. Ketika jurnalis mengabaikan prinsip-prinsip itu, tanpa disadari ia sedang menggali kuburnya sendiri.
***
Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Jika hendak membuat program tentang Pesantren, redaksi sebaiknya melibatkan tokoh pesantren sejak riset dan pra-produksi. Wartawan harus datang langsung ke lapangan, ikut “mengaji”, memahami dan mendalami pesantren dari dalam. Kiranya dirasa perlu juga ada semacam panduan khusus “etika peliputan” untuk lembaga keagamaan.
Jurnalis harus belajar dari para kiai tentang adab dan konteks. Para kiai juga perlu memahami cara kerja media. Pesantren juga perlu terbuka. Dunia digital tidak dapat dihindari. Banyak pesantren yang sudah mulai mengelola narasinya sendiri. Ada yang membuat film dokumenter, menulis kisah santri, bahkan membuat kanal YouTube yang menampilkan kegiatan pesantren. Langkah-langkah kecil tersebut akan membantu publik melihat pesantren secara utuh.
Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama. Media harus belajar lebih sensitif dan teliti. Pesantren belajar lebih terbuka dan komunikatif. Masyarakat belajar untuk tidak cepat bereaksi tanpa memahami konteks. Kalau semua pihak mau belajar, luka ini dapat berubah menjadi ruang perbaikan bersama.
Media harus menjadi jembatan penghubung antara publik dan pesantren, merekognisi dan mengamplifikasi setiap jejak pengabdian, peran, dan kontribusi pesantren bagi bangsa dan negara. Cara media memperlakukan dan memberitakan pesantren, menunjukkan seberapa besar media menghargai sejarah, aset, akar budaya, dan nilai spiritual bangsanya sendiri, tanpa kehilangan nalar kritisnya.
Tatang Astarudin, Pimpinan Pondok Pesantren Universal Al-Islamy Bandung dan Pesantren Al-Kahfi Cirebon, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas KH Ruhiat (UNIK) Cipasung, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)