Memaknai Kata-kata Zahra di Saat RK – Atalia Proses Cerai
- account_circle Tim Redaksi
- calendar_month Ming, 28 Des 2025
- comment 0 komentar

KALBAR Kanal31.com — Ketika ayah dan ibu sudah tidak ada lagi aura kasih, anak selalu menjadi korban. Begitulah yang dirasakan oleh Zahra, anak dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Ia menulis puisi mencurahkan isi hatinya. Simak ungkapan hati Zahra sambil seruput Koptagul, wak!
Ada kata-kata yang lahir bukan dari pikiran, melainkan dari reruntuhan batin. Ia tidak disusun untuk indah, tidak dirancang agar rapi, tetapi mengalir seperti darah dari luka yang terlalu lama ditutup senyum. Unggahan Zahra adalah jenis tulisan yang tidak mengetuk pintu nurani, melainkan mendobraknya, lalu duduk di tengah puing-puing dengan tenang, seolah berkata, inilah sisa-sisa yang kalian minta untuk kulihatkan.
Tulisan itu tidak berisik, tetapi menggelegar. Tidak panjang, tetapi beratnya seperti kitab pengakuan dosa. Setiap kalimat terasa seperti palu yang dipukulkan ke dinding sunyi bernama keluarga, hukum, dan keadilan. Zahra tidak sedang menulis status. Ia sedang menggelar pengadilan batin, tanpa hakim, tanpa pembela, tanpa hukum acara, hanya ada luka dan Tuhan.
“Ayah, jika keadilan bumi enggan menghukummu.”
Kalimat ini seperti pintu yang ditutup pelan, tetapi meninggalkan gema panjang. Di sana, ada pengakuan getir, keadilan dunia kerap lelah berjalan, tertatih ketika harus mengejar mereka yang punya nama, kuasa, dan sejarah panjang jasa. Zahra seakan berkata, bumi ini punya hukum, tapi tidak selalu punya keberanian. Maka ia berhenti berharap pada palu hakim, lalu mengangkat wajah ke langit.
“Maka biarlah setiap helai rambutku yang terbuka menjadi saksi.”
Di titik ini, kesedihan berubah menjadi ironi yang kejam. Tubuh perempuan, yang selama ini paling mudah dijadikan objek moral, sasaran dosa, dan panggung penghakiman, ia jadikan arsip perlawanan. Rambut, yang kerap diperdebatkan, dipolitisasi, dan diseret ke mimbar-mimbar moral, justru dihadirkan sebagai saksi bisu. Zahra seolah berkata, jika aku selalu disalahkan, biarlah kesalahanku menjadi bukti. Jika aku selalu dituding, biarlah tudingan itu kubalikkan menjadi cermin.
“Menyeretmu ke pengadilan Tuhan.”
Inilah klimaks spiritual dari keputusasaan. Ketika dunia terlalu kecil untuk menampung kebenaran, manusia sering kali melemparkannya ke akhirat. Tuhan menjadi hakim terakhir, tempat keadilan tidak bisa disuap, tidak bisa ditunda, tidak bisa dinegosiasikan. Tetapi kalimat ini juga mengandung tragedi, betapa seorang anak harus sejauh itu melangkah, melewati ayahnya, melewati hukum, melewati dunia, hanya untuk berharap pada keadilan.
“Nikmatilah dunia sebagaimana kau menikmati pengkhianat yang merobek keluarga kita.”
Kalimat ini tidak marah. Ia dingin. Justru karena itu ia menusuk. Kata keluarga di sini tidak hadir sebagai rumah, melainkan sebagai medan perang. Ada pengkhianatan, ada luka, ada sesuatu yang hancur dari dalam. Ini bukan drama sinetron, tetapi tragedi klasik: rumah yang megah dari luar, tetapi retak di fondasi. Seperti semua tragedi besar, yang paling menderita justru mereka yang tidak pernah memilih peran.
“Sementara aku perlahan menenun jubah api untukmu, melalui tiap-tiap dosaku yang sengaja kupamerkan pada dunia.”
Ini adalah hiperbola paling menyedihkan. Zahra menjadikan dirinya altar pengorbanan. Dosanya, atau apa pun yang dunia cap sebagai dosa, dirajut menjadi jubah api. Ia sadar, publik gemar menyaksikan kehancuran personal sebagai hiburan. Maka ia menyuguhkannya, dengan pahit, dengan sadar, seolah berkata, jika lukaku adalah tontonan, maka saksikan sampai kalian lelah.
Unggahan itu pun viral. Media sosial berubah menjadi ruang sidang dadakan. Ada yang bersimpati, ada yang menghakimi, ada yang pura-pura bijak sambil tetap menikmati dramanya. Semua bicara, semua menafsir, semua merasa paling tahu. Padahal, yang berbicara sesungguhnya hanyalah seorang anak yang lelah memikul konflik orang dewasa.
Sampai hari ini, tidak ada klarifikasi. Tidak ada penjelasan. Keheningan itu justru menjadi gema paling keras. Diam, dalam konteks ini, bukan netral. Ia adalah ruang kosong yang diisi prasangka, spekulasi, dan luka yang semakin membusuk.
Zahra, atau lengkapnya Camillia Laetitia Azzahra. Ia lahir di Bandung, 17 Agustus 2004. Ia tumbuh di persimpangan yang tidak pernah ia pilih. Antara privasi dan sorotan, antara menjadi anak biasa dan simbol keluarga publik. Ia menekuni seni, bernyanyi di The Voice Kids, belajar arsitektur di ITB dan Newcastle University, Inggris. Ia peka, kreatif, dan seperti tampak dalam tulisannya, memiliki kepekaan filosofis yang lahir dari kehilangan, termasuk kepergian sang kakak, Eril, yang lebih dulu meninggalkan duka mendalam.
Tulisan Zahra bukan sekadar curahan emosi. Ia adalah potret generasi yang tumbuh di era di mana luka pribadi mudah menjadi konsumsi publik. Ia adalah kritik diam-diam terhadap dunia yang gemar menuntut klarifikasi, tetapi malas mendengarkan rasa sakit.
Pada akhirnya, ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia tentang betapa rapuhnya keadilan ketika berhadapan dengan kuasa. Tentang keluarga yang bisa runtuh tanpa suara. Tentang seorang anak yang terpaksa berbicara karena diam tidak lagi cukup.
Mungkin, di sanalah makna terdalamnya bersemayam. Di balik nama besar, jabatan tinggi, dan citra yang dibangun bertahun-tahun, selalu ada manusia yang bisa terluka. Ketika luka itu akhirnya berbicara, ia tidak meminta pengadilan. Ia hanya meminta didengar, sebelum berubah menjadi api yang tak lagi bisa dipadamkan.
Foto Ai hanya ilustrasi
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
- Penulis: Tim Redaksi






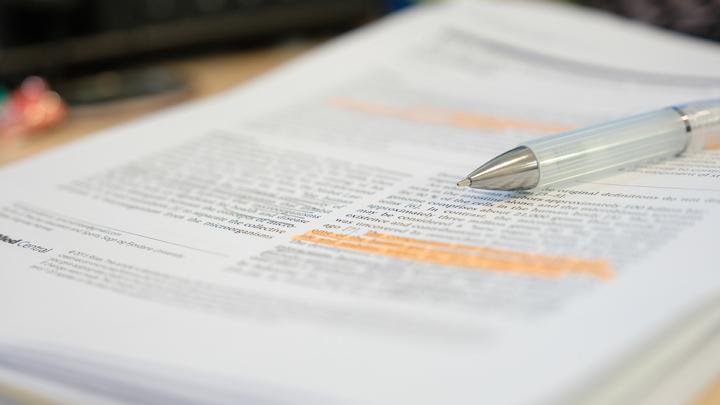











Saat ini belum ada komentar